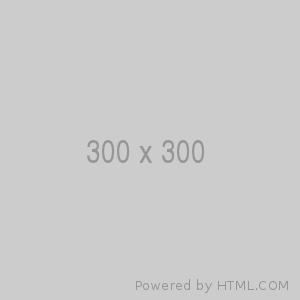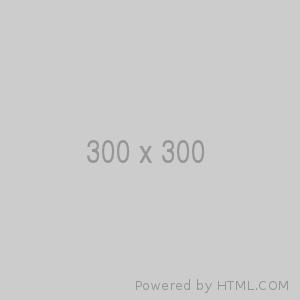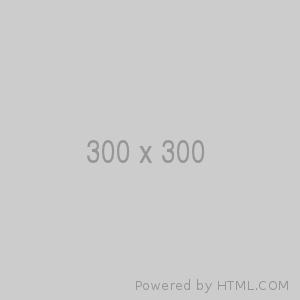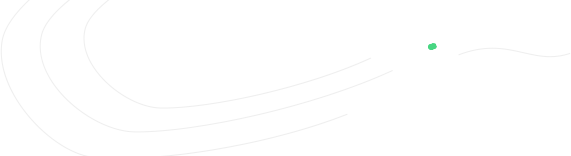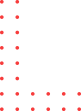Namaku Rona, lengkapnya Rona Jingga semesta. Orang-orang menyebut ku kutu buku, Karena tidak ada tempat lain selain perpustakaan yang menjadi sasaran nongkrong sehari-hari ku. Sebenarnya, sebutan itu tidak pas. Aku lebih berlegowo jika disebut sebagai kutu novel, karena apa yang ku baca di perpustakaan hanyalah novel, tidak selayaknya seperti kutu buku pada umumnya yang berkutat dengan buku-buku ilmiah. Bagiku, buku ilmiah sangatlah membosankan. Tidak ada gambar, mononton, bahasanya formal dan kaku. Dan bagiku, novel sangatlah menarik. Pengeksekusian ide yang apik, alur cerita yang tersusun secara baik hingga mampu menghasilkan berjuta imajinasi di kepala pembaca.
Menurutku, membaca novel lebih seru dibanding menonton film. Saat menonton film, kita hanyut dalam setiap scene yang ditampilkan sebagai hasil karya si sutradara. Sedangkan saat kita membaca novel, setiap adegan yang sedang kita baca akan bermain dalam sebuah scene dalam imajinasi kita sendiri secara otomatis. Kitalah sutradaranya.
Selain kutubuku, image yang melekat pada diriku selanjutnya adalah diriku yang pendiam. Aku yakin, setiap manusia terlahir ke dunia dengan dikaruniai masing-masing sifat dan karakter. Dan kebetulan, Allah menganugerahi sifat pendiam untukku.
Aku tidak kecewa jadi seorang pendiam, aku malah bersyukur.
Ada begitu banyak orang yang memiliki sifat aktif bicara, namun aku kira keaktifan bicara yang mereka miliki kebanyakan justru mengundang banyak dosa. Orang yang aktif berbicara atau bisa disebut bawel atau juga bisa disebut orang yang tidak bisa diam cenderung berbicara sesuka hati mereka. Mereka tidak peduli ada begitu banyak hati yang tidak terlihat yang sedang merasa.
Aku tidak kecewa jadi seorang pendiam, aku malah bersyukur.
Ada begitu banyak orang yang memiliki sifat aktif bicara, namun aku kira keaktifan bicara yang mereka miliki kebanyakan justru mengundang banyak dosa. Orang yang aktif berbicara atau bisa disebut bawel atau juga bisa disebut orang yang tidak bisa diam cenderung berbicara sesuka hati mereka. Mereka tidak peduli ada begitu banyak hati yang tidak terlihat yang sedang merasa.
Hati seseorang siapa yang tahu? Jangankan untuk si pendiam, sesama talk active saja kita tidak tahu potensial yang akan dirasakan hati masing-masing.
Contohnya, seperti yang tak sengaja kudengar dari sesama perempuan yang tengah duduk berhadapan di sebelahku.
Contohnya, seperti yang tak sengaja kudengar dari sesama perempuan yang tengah duduk berhadapan di sebelahku.
“eh, atuh sia mah eta ngetikna nuhade! Meuni acak-acakan kieu,” ujar salah seorang berkacamata dengan niat mengoreksi hasil ketikan temannya yang berrambut ikal.
Namun, tak disangka koreksian itu mengundang ketidaksukaan si rambut ikal. Sesaat wajahnya menampakkan kekesalan, sampai dia berujar kata-kata menyakitkan ini dengan setengah bercanda setengah menyindir, “Heleh ngke atuh pan bakal diedit! Kami geh ngarti, mejeuh sia mah urusan bae kacamata sorangan tah! Haha.”
Kuputuskan untuk pindah tempat duduk. Aku memilih untuk duduk di salah satu bilik untuk membaca.
Hhh.. ini jauh lebih baik.
Namun, tak disangka koreksian itu mengundang ketidaksukaan si rambut ikal. Sesaat wajahnya menampakkan kekesalan, sampai dia berujar kata-kata menyakitkan ini dengan setengah bercanda setengah menyindir, “Heleh ngke atuh pan bakal diedit! Kami geh ngarti, mejeuh sia mah urusan bae kacamata sorangan tah! Haha.”
Kuputuskan untuk pindah tempat duduk. Aku memilih untuk duduk di salah satu bilik untuk membaca.
Hhh.. ini jauh lebih baik.
Dari kejadian tadi, siapa yang akan menyangka kritikan yang sifatnya membangun justru bakal membuat kesal? Dan siapa yang tahu, balasan sindiran dari si ikal akan sangat menyakiti hati si kacamata?
Untuk itu, aku bersyukur.
Untuk itu, aku bersyukur.
Kutatap judul pada sampul sebuah novel karangan Emma Grace.
RE-WRITE.
“Write” yang berarti “tulis”.
Bagi kebanyakan orang pendiam, menulis adalah salah satu media untuk menyalurkan apa yang ada di kepala mereka yang tidak bisa diungkapkan melalui obrolan atau ucapan. Menulis adalah hobi lain bagiku.
RE-WRITE.
“Write” yang berarti “tulis”.
Bagi kebanyakan orang pendiam, menulis adalah salah satu media untuk menyalurkan apa yang ada di kepala mereka yang tidak bisa diungkapkan melalui obrolan atau ucapan. Menulis adalah hobi lain bagiku.
Banyak hal yang kutulis. Mulai dari mama, papa, kakak, aku, sekolahku, kuliahku, mata kuliah hari ini, kegundahanku, kegalauanku, kebahagiaanku, dan satu hal lain yang selalu kutulis tanpa pernah lupa satu haripun, yaitu senja. Semburat jingga di langit pertanda pergantian siang dan malam. Perbatasan antara lelah dan lelap.
Senja yang selalu temaram, dan romantis. Mengantarkan aku pada satu memori indah yang terselip di antara beribu celah hatiku. Bersamanya, di satu senja 25 Maret lalu.
Senja yang selalu temaram, dan romantis. Mengantarkan aku pada satu memori indah yang terselip di antara beribu celah hatiku. Bersamanya, di satu senja 25 Maret lalu.
SENJA DUA MINGGU LALU
25 Maret 2017
Sebuah novel berada dalam genggamanku seraya kulangkahkan kakiku menuju halte yang terletak di depan kampus tempat aku menuntut ilmu. Tujuanku adalah pergi ke perpustakaan daerah yang terletak sekitar 300 meter dari sini.
Setelah menyebrangi dua lajur jalan raya, ada seorang perempuan yang tengah duduk di posisi tengah, dan tampaknya sedang menunggu angkutan —atau motor jemputan, karena ia membawa helm.
25 Maret 2017
Sebuah novel berada dalam genggamanku seraya kulangkahkan kakiku menuju halte yang terletak di depan kampus tempat aku menuntut ilmu. Tujuanku adalah pergi ke perpustakaan daerah yang terletak sekitar 300 meter dari sini.
Setelah menyebrangi dua lajur jalan raya, ada seorang perempuan yang tengah duduk di posisi tengah, dan tampaknya sedang menunggu angkutan —atau motor jemputan, karena ia membawa helm.
Kududuki bangku di sisi kanan perempuan itu. Tak lama, sebuah motor yang dikemudikan seorang laki-laki berhenti di depan kami, menjemput perempuan yang duduk di sebelahku. Dengan raut wajah bahagia perempuan itu berlari menghampiri laki-laki itu, lalu seketika saja mereka pergi.
Tinggal aku sendirian di halte. Angkot tak biasanya lama. Kutatap gedung yang berada di seberang mata —kampusku—, melihat begitu banyak orang hilir mudik dengan masing-masing urusannya. Ada yang tampak tergesa-gesa, ada yang terlihat begitu keberatan dengan tas bawaannya, ada yang terlihat santai mendenarkan musik atau entah apa lewat headset, ada yang tertawa bersama temannya, ada yang tampak murung, ada yang biasa saja, ada yang terlihat ceria dan bersahaja.
Tiba-tiba, aku teringat akan sebuah novel yang sedari tadi kugenggam. Judulnya, SAUJANA HATI.
Untuk mengusir rasa bosan menunggu angkot yang tak kunjung tiba, aku memutuskan untuk membuka halaman demi halaman dan mulai membacanya.
Dan itu berlangsung cukup lama.
Mungkin ada beberapa atau bahkan begitu banyak angkot yang lewat dan berhenti —aku pun mendengar bunyi klaksonnya dan tawaran sang abang supir kepadaku— tapi, aku terlalu fokus dengan satu benda di hadapan mataku —novel, sebelum aku menyadari ada sebuah binder merah tergeletak di sisiku.
Untuk mengusir rasa bosan menunggu angkot yang tak kunjung tiba, aku memutuskan untuk membuka halaman demi halaman dan mulai membacanya.
Dan itu berlangsung cukup lama.
Mungkin ada beberapa atau bahkan begitu banyak angkot yang lewat dan berhenti —aku pun mendengar bunyi klaksonnya dan tawaran sang abang supir kepadaku— tapi, aku terlalu fokus dengan satu benda di hadapan mataku —novel, sebelum aku menyadari ada sebuah binder merah tergeletak di sisiku.
“Punya siapa?”, hatiku bertanya-tanya.
Mungkinkah binder ini milik si perempuan tadi? Tapi kupikir bukan, karena dengan hati-hati kubuka cover binder tersebut dan tertulis nama sang empunya.
Sebuah nama seseorang yang aku dan hatiku mengenalnya.
Mungkinkah binder ini milik si perempuan tadi? Tapi kupikir bukan, karena dengan hati-hati kubuka cover binder tersebut dan tertulis nama sang empunya.
Sebuah nama seseorang yang aku dan hatiku mengenalnya.
Sesaat, aku bingung, apa yang harus kulakukan? Terbersit pikiran untuk membiarkan binder tersebut di sini sementara aku pergi ke perpustakaan daerah. Toh, di sini aman, tidak akan apa-apa. Tapi, batinku yang lain menyuruku agar mengembalikan kepada sang pemilik, atau paling tidak menyerahkannya ke pos satpam.
Aku ragu. Namun akhirnya kuputuskan untuk menunggu dahulu. Barangkali dia sadar akan bindernya yang hilang dan mencarinya ke sini.
Untungnya, ada novel. Jadi, aku tidak perlu menelan rasa bosan sendirian.
Aku ragu. Namun akhirnya kuputuskan untuk menunggu dahulu. Barangkali dia sadar akan bindernya yang hilang dan mencarinya ke sini.
Untungnya, ada novel. Jadi, aku tidak perlu menelan rasa bosan sendirian.
Semilir angin cukup sejuk di petang ini. Langit mulai menampakkan perubahannya. Putih kebiruan perlahan mulai memerah membentuk jingga kekuningan yang indah.
Cukup lama aku menunggu sang empunya datang, namun ternyata sia-sia.
Senja mulai datang, dan aku memutuskan untuk membawa binder ini ke pos satpam kampus.
Cukup lama aku menunggu sang empunya datang, namun ternyata sia-sia.
Senja mulai datang, dan aku memutuskan untuk membawa binder ini ke pos satpam kampus.
Namun, saat tanganku sudah menggamit ujung binder, suara langkah terdengar dari ujung. Seorang laki-laki yang tampak seperti siluet menghampiri. Napasnya tersengal saat berhenti tepat 2 meter dariku.
Laki-laki itu, menghalangi sinar matahari senja. Walau begitu aku masih bisa melihat wajahnya meskipun samar.
“afwan, apa itu binder ana?”, Tanya laki-laki itu.
Aku tau ini bindernya, karena aku tahu dia.
Laki-laki itu, menghalangi sinar matahari senja. Walau begitu aku masih bisa melihat wajahnya meskipun samar.
“afwan, apa itu binder ana?”, Tanya laki-laki itu.
Aku tau ini bindernya, karena aku tahu dia.
Dia adalah irfan, kakak angkatan sekaligus senior satu jurusan. Satu-satunya laki-laki yang kukagumi dalam diam. Akhlaknya memancarkan pribadi yang sholih, senyumnya selalu tak pernah pudar, kecerdasan, dan bawaannya yang sederhana tak mampu mencegah kecenderungan hati ini padanya.
Jujur, aku tak berharap hal ini akan terjadi. Aku selalu berusaha menghindar darinya. Berusaha untuk sebisa mungkin tidak berpapasan, bahkan tidak melihatnya.
Jujur, aku tak berharap hal ini akan terjadi. Aku selalu berusaha menghindar darinya. Berusaha untuk sebisa mungkin tidak berpapasan, bahkan tidak melihatnya.
Aku tidak mau salah menyikapi hati yang terus-terusan berbicara ini. Dan karena cinta itu fitrah, maka kukembalikan rasa yang entah ini cinta atau apa kepada-Nya Sang Maha Membolak-balikkan hati.
“siapa nama akhi?”, kutanyakan hal itu hanya untuk menutupi apa yang selama ini terjadi padaku —aku tahu namanya, aku tahu dia aktif di berbagai organisasi dan aku tau.. dia suka senja, sama sepertiku.
“Irfan Pramudya, benarkah itu binder ana?” jawabnya.
Kuanggukkan kepalaku, dan kutundukkan. Kuserahkan binder merah itu dan ia menerimanya.
“Irfan Pramudya, benarkah itu binder ana?” jawabnya.
Kuanggukkan kepalaku, dan kutundukkan. Kuserahkan binder merah itu dan ia menerimanya.
“Syukron ukhti, syukron katsir,” aku melirik sekilas padanya untuk menghargai. Dan yang tertangkap oleh lensa mataku adalah ia yang tengah menundukkan pandangan.
“afwan, bukan maksud apa-apa. tadinya mau ana kasih ke pos satpam. Tapi Alhamdulillah” , ujarku hati-hati.
“tidak apa-apa, terimakasih sekali lagi.”
Aku mengangguk, dan melangkahkan kakiku yang sedari tadi ingin berlari menembus senja dan berteriak dalam hati.
“afwan, bukan maksud apa-apa. tadinya mau ana kasih ke pos satpam. Tapi Alhamdulillah” , ujarku hati-hati.
“tidak apa-apa, terimakasih sekali lagi.”
Aku mengangguk, dan melangkahkan kakiku yang sedari tadi ingin berlari menembus senja dan berteriak dalam hati.
DI SITU AKU TAHU
Kusujudkan hatiku hanya pada-Nya. Memendam cinta tidaklah seburuk apa yang kusangka. Karena do’a bahkan lebih indah daripada janji dan kata-kata.
Kusujudkan hatiku hanya pada-Nya. Memendam cinta tidaklah seburuk apa yang kusangka. Karena do’a bahkan lebih indah daripada janji dan kata-kata.
Dua minggu lalu itu, cukup sekali saja itu terjadi.
Dua minggu lalu itu, darinya aku tak ingin mengulangnya.
Sejak dua minggu yang lalu, aku semakin tak ingin berpapasan atau melihatnya.
Karena aku takut salah jika aku melihatnya dan mengakui bahwa memang ini adalah cinta.
Dua minggu lalu itu, darinya aku tak ingin mengulangnya.
Sejak dua minggu yang lalu, aku semakin tak ingin berpapasan atau melihatnya.
Karena aku takut salah jika aku melihatnya dan mengakui bahwa memang ini adalah cinta.
Kuambil secarik kertas yang sejak saat itu kusimpan, entah yang kulakukan ini benar atau justru salah. Yang jelas, aku berjanji akan mengembalikan ini padanya.
Ini, secarik kertas miliknya.
Ini, secarik kertas yang tak sengaja kulihat terselip di belakang sebuah binder merah miliknya.
Ini, secarik kertas yang membuat semakin banyak sujud yang kulakukan di sepertiga malam. Karena ini, adalah jawaban.
Ini, secarik kertas miliknya.
Ini, secarik kertas yang tak sengaja kulihat terselip di belakang sebuah binder merah miliknya.
Ini, secarik kertas yang membuat semakin banyak sujud yang kulakukan di sepertiga malam. Karena ini, adalah jawaban.
“Untuk senja yang selalu membuatku merona..
Puitis dan romantis bukanlah sifatku, tapi untuk ini, aku tak kuasa menahannya.
Sebuah rasa suci, yang baru kali ini aku merasakannya.
Puitis dan romantis bukanlah sifatku, tapi untuk ini, aku tak kuasa menahannya.
Sebuah rasa suci, yang baru kali ini aku merasakannya.
Hai, senja merona..
Diam-diam aku membaca apa yang kau baca, dan aku selalu berharap kau tidak menyadarinya.
Diam-diam juga aku tahu bahwa kau menyukai senja.
Dan sejak saat itu, aku menyukai semburat jingga di ufuk barat dikala petang datang. Aku suka senja, dan bagiku kau adalah senja itu.
Diam-diam aku membaca apa yang kau baca, dan aku selalu berharap kau tidak menyadarinya.
Diam-diam juga aku tahu bahwa kau menyukai senja.
Dan sejak saat itu, aku menyukai semburat jingga di ufuk barat dikala petang datang. Aku suka senja, dan bagiku kau adalah senja itu.
Kau tak tahu ada debu yang diam-diam mengagumimu, dan menaruh harapannya dalam doa untukmu.
Diammu meneduhkan. Dan aku, dalam diam pula memendam rasa ini untukmu.
Diammu meneduhkan. Dan aku, dalam diam pula memendam rasa ini untukmu.
Mungkin terlalu cepat aku menyimpulkan rasa ini, tapi kurasa benar.. tak ada yang perlu diragukan, aku tahu bahwa aku mencintai sosok senja yang merona. Dan suatu hari, kau perlu tahu ini semua.
Tetaplah dengan diammu, aku akan datang suatu hari dan menjadi senja abadi untukmu.
Tetaplah dengan diammu, aku akan datang suatu hari dan menjadi senja abadi untukmu.