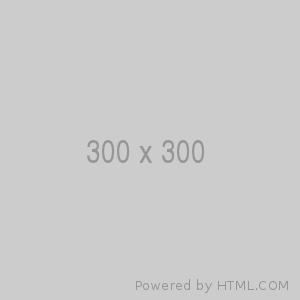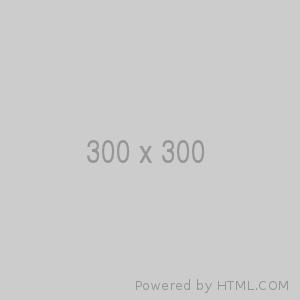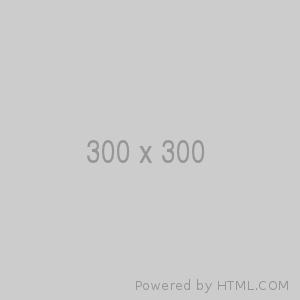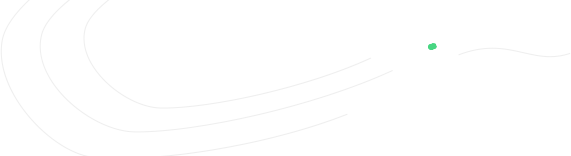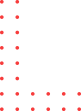Bagi saya, menulis merupakan sebuah persetubuhan manusia dengan pengalaman empiris, dan semua orang sedianya selalu menyayangkan bila sebuah persetubuhan tidak sampai pada titik jenuh yang kita sebut klimaks. Menulis bukan hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saja, lebih dari itu ia merupakan buah dari kesungguhan menyusun kata dan kalimat, menggali apa yang tertanam dalam pita otak serta memilah-milah berbagai pengalaman dan perasaan untuk dijadikan satu kesatuan yang utuh.
Bagi saya, menulis merupakan sebuah persetubuhan manusia dengan pengalaman empiris, dan semua orang sedianya selalu menyayangkan bila sebuah persetubuhan tidak sampai pada titik jenuh yang kita sebut klimaks. Menulis bukan hanya menyampaikan apa yang ada di pikiran saja, lebih dari itu ia merupakan buah dari kesungguhan menyusun kata dan kalimat, menggali apa yang tertanam dalam pita otak serta memilah-milah berbagai pengalaman dan perasaan untuk dijadikan satu kesatuan yang utuh.Ada banyak term yang bisa kita pakai untuk kegiatan ini (menulis), dan salah satu yang menjadi favorit saya adalah term literasi. Perkenalan saya dengan dunia literasi, bisa terbilang cukup lama. Mulanya dimulai dari kebahagiaan saya jikala saya mampu menyelesaikan suatu bacaan, baik bacaan yang pendek maupun bacaan yang panjang.
Saya ingat, ketika Sekolah Menengah Pertama, saya sudah membaca karya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Setelah selesai membaca novel tebal untuk pertama kalinya, saya rasa saat itu saya sudah jatuh ke dalam perasaan yang indah. Ya saya jatuh cinta dengan cerita-cerita. Setelah jatuh cinta pada cerita, saya kemudian membaca karya-karya Habiburrahman El-Shirazy, dari Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-ayat Cinta dan Dalam Mihrab Cinta yang akhirnya membuat saya sedih sesedih-sedihnya. Saya tidak tahu ketika itu, kalau tulisan mampu menyentuh sisi avektif seseorang.
Yang perlu disayangkan ketika itu adalah saya tidak pernah berpikir bagaimana caranya menulis?!
Di awal-awal saya membaca, saya memang hanya bertemu dengan karya-karya dua novelis itu saja. Karena memang tidak ada yang menyarankan saya untuk kemudian langsung membaca Pramoedya Ananta Toer, Budi Darma, Umar Kayam, Putu Wijaya, atau penulis luar seperti Ernest Himingway, Garcia Marquez, Kafka atau bahkan Dan Brown. Saya mengenal mereka bertahun-tahun setelahnya, atau ketika saya kemudian memutuskan untuk mondok di TMI Al-Amien Prenduan. Di sinilah saya kemudian membayar tuntas pencarian saya selama ini.
Tahun pertama mondok di TMI, sebenarnya hanya saya habiskan buat main-mainsaja. Tahun pertama saya sebenarnya tidak begitu membahagiakan. Saya berteman dengan Umar Faruq, santri yang masuk pondok karena dijanjikan oleh bapaknya akan dibelikan motor Ninja, atau Harun Ar-Rasyid, anak medan yang senang membicarakan hal-hal yang luks seperti sepatu Nike original yang ia beli dengan harga yang sangat fantastis, atau tentang koleksi baju, kalung, cincin dan Gadget yang saya rasa tidak biasa, juga sama halnya dengan Romy Fredyanto, anak Sunda yang suka merokok dan senang membicarakan pengalaman birahinya dengan pacar-pacarnya terdahulu. Bersama mereka saya menghabiskan tahun pertama saya di TMI, tidak ada yang berkembang dalam dunia akademik dan soft skill,sebelum akhirnya mereka satu per satu terbuang dan memilih pergi sehingga tersisa saya sendirian.
Di sinilah saya kemudian bertemu dengan Saifir Rahman, sosok pemikir keras, atau Rahmad Syah Dewa sosok tangguh dalam mendalami sesuatu dan Nawaf Muhyi sosok bersahaja yang senang sekali mengulang-ulang nasihat ibunya dengan Bahasa Sunda. Mereka mengenalkan saya pada Sanggar Sastra Al-Amien (SSA), mereka mengenalkan pada saya dunia penerbitan untuk pemula dan bersama mereka pula saya menikmati hari-hari saya di pesantren. Di sinilah pesantren menjadi candu yang susah saya lepaskan begitu saja—dan yang tidak akan saya lepas, selamanya— dan akhirnya membuat saya mengagumi dunia pesantren sampai saat ini.
Bersama mereka pula kemudian saya mengenal Nurcholis Madjid, sosok guru Bahasa Indonesia yang rela meluangkan waktu untuk mengoreksi cerpen-cerpen dan karya saya yang lain, Hamzah Arsa yang mengajarkan saya banyak hal tentang kerja keras, belajar otodidak juga mengenalkan saya dengan dunia penelitian. Saya kemudian terlibat intens dengan dunia kepenulisan dan penerbitan. Mereka menyodorkan saya Dostoyevski, Garcia Marquez, Paulo Coelho dan lainnya. Mereka juga melibatkan saya dalam redaksi Senja Media Coretan Pena, Lima Khazanah Literasi, dan yang terakhir mau tidak mau saya akhirnya belajar editing dan layouting untuk penerbitan WARKAT tahunan TMI Al-Amien Prenduan.
Saya mengenang perjalan sebagai salah satu cara berterima kasih. Kenang-kenangan saya kemudian berkelindan, satu per satu menjadi cerita utuh. Di sinilah saya menikmati persetubuhan unik manusia dan pengalaman empiris. Saya ingat apa yang Pramodya Ananta Toer ucapkan, Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.(i)
*Imam Assodiq adalah alumni Al-Amien Prenduan. Saat ini sibuk mengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, sembari aktif di Qalami Khazanah Literasi Santri, salah satu media dan wadah untuk melatih dan mengembangkan budaya baca tulis.